KATA
PENGANTAR
Bismillahirrahmannirrahim
Syukur
dan puji yang tidak terhingga kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan
kemurahan – Nya jua, dapatlah kami menyerahkan makalah ini.
Maksud
saya yang terutama dalam menyerahkan makalah ini ialah untuk bahan pegangan
atau tambahan literatur bagi para mahasiswa dan masyarakat. Pada masa sekarang
ini amatlah terasa banyak sumber – sumber yang bisa menjadi pelajaran. Akan
tetapi banyak yang salah mempergunakannya.
Terima
kasih yang sebanyak – banyaknya dan mudah – mudahan Allah SWT tetap memberikan
taufiq dan hidayah kepada kita sekalian, Amin....
Wassalam,
Penulis
DAFTAR
ISI
Kata Pengantar...................................................................................................
Daftar Isi..............................................................................................................
BAB I PENDAHULUAN...........................................................................................
BAB II PEMBAHASAN.............................................................................................
a) Pengertian
Skeptisisme.............................................................................
b) Munculnya
skeptisisme..............................................................................
c) Jenis-jenis
skeptisisme...............................................................................
d) Teori-teori skeptisisme...............................................................................
e)
Hubungan skeptisisme dengan ilmu...........................................................
BAB III KESIMPULAN DAN PENUTUP......................................................................
Daftar Pustaka.........................................................................................................
BAB I
PENDAHULUAN
1.
Latar
belakang
Kelekatan tanpa syarat antara
pikiran dan kenyataan, dan hal itu tentu saja perlu ditekankan. Adanya
pengetahuan merupakan suatu hal yang pokok dan tak dapat direduksikan. Pikiran
ada, dan adanya pikiran merupakan kesaksian bagi dirinya sendiri mengenai
keterbukaannya terhadap ada. Tidak ada keraguan atau penyangkalan terhadap
keterbukaan ini yang dapat dipertahankan.
Menurut seorang skeptik absolut,
pikiran manusia tidak dapat mencapai kebenaran objektif. Sebab justru usahanya
untuk menyatakan keyakinannya sendiri melibatkan penyangkalan terhadap
keyakinannya itu.
2. Rumusan masalah
a.
Apa pengertian
skeptisisme ?
b.
Bagaimana
munculnya skeptisisme ?
c.
Apa jenis-jenis skeptisisme
?
d.
Apa teari-teori
skeptisisme ?
e.
Apa hubungannya
skeptisisme dengan ilmu ?
3. Tujuan
Dalam pembuatan makalah ini
bertujuan untuk menjelaskan segala sesuatu yang berhubungan dengan skeptisisme.
BAB II
PEMBAHASAN
1.
Pengertian
Skeptisisme
Skeptisisme
berasal dari bahasa Yunani “skeptesthai” yang berarti menguji,
menyelidiki, mempertimbangkan. Ia merupakan pandangan filosofis yang mengatakan
bahwa mustahil bagi manusia untuk mengetahui segala sesuatu secara absolut. Kaum skeptis selalu
meragukan setiap klaim pengetahuan, karena memiliki sikap tidak puas dan masih
mencari kebenaran. Sikap tersebut didorong oleh menyebarnya rasa
ketidaksepakatan yang tiada akhir terhadap sebuah isu fundamental. Jadi
skeptisisme sangat erat kaitannya dengan sikap keragu-raguan terhadap segala
sesuatu.[[1]]
Istilah “skeptisisme” berasal dari kata yunani
yaitu skeptomai yang secara harfiah pertama-tama berarti “saya meragukan.” Para
filsuf Yunani Kuno di buat bertanya-tanya oleh adanya beberapa gejalah
pengalaman keindraan, seperti ilusi, mimpi, halusinasi yang kadang sulit
dibedakan dari persepsi keindraan kita yang “normal”
terhadap benda-benda fisik.[2]
Sejak zaman klasik hingga sekarang, para
skeptis telah mengembangkan argumen untuk meruntuhkan pendapat para filosuf
dogmatis, scientist, dan para teolog. Di zaman klasik misalnya, kaum
skeptis menentang klaim pengetahuan Platonisme, Aristotelianisme, dan
Stoikisme. Di era renaissance, mereka menentang Scholasticism
dan Calvinism. Setelah zaman Descartes, skeptisisme menyerang Cartesianism.
Pada era berikutnya, serangan skeptisisme ditujukan pada Kantianisme dan
Hegelianisme. Pada abad pencerahan, skeptisisme diartikan menjadi sebuah sikap
ketidakpercayaan –khususnya dalam masalah agama–, yang pada gilirannya, kaum
skeptis disamakan dengan ateis.[3]
Dari
beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa skeptisisme merupakan
penalaran pikiran yang tidak bisa nyata dalam imajinasi kita hanya bisa di
lihat dari mimpi, halusinasi kesadaran kita, dll.
2. Munculnya skeptisisme
Dalam
sejarah, Skeptisisme mengambil banyak bentuk dan warna. Mereka berbeda-beda,
baik dalam tema, lingkup maupun bobot keraguannya. Mengenai tema, pada zaman
Yunani Kuno sudah di kenal kelompok akademisi dan kelompok Pyrrhonian. Kelompok
yang pertama, dengan tokohnya seperti Arcesilaus ( 315-241 ) dan Carneades (
214-129 ), mengajarkan bahwa tidak ada pernyataan yang pasti mengenai apa yang
sedang terjadi selain apa yang secara langsung dialami. Ke,lompok yang kedua
yang dipelopori oleh Poleh Pyrrho dari
Elis ( 360-270 ) dan kemudian diteruskan pada zaman Romawi oleh Sextus
Empiricus ( sekitar tahun 250 Masehi ) tidak menyangkal bahwa pengetahuan
mengenai apa yang tidak secara langsung dialami, dan mengenai apa yang tidak
langsung jelas dengan sendirinya, itu mungkin. Yang mereka ajarkan adalah
perlunya menangguhkan penilaian dan putusan kita terhadap ajaran tentang
hakikat kenyataan. Menurut mereka kita lebih baik hidup menurut apa yang tampak
saja dan berusaha memelihara ketenangan pikiran.[4]
Dari
beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa skeptisisme dalam sejarahnya
merupakan imajinasi seorang ilmuan yang merupakan ide-ide yang logis dalam
pemikirannya itu sendiri.
3. Jenis-jenis
skeptisisme
Sekeptisisme
hanya dibedakan berdasarkan tema keraguannya, tetapi juga berdasarkan lingkup
bidang yang diragugannya. Biasa dibedakan antara skeptisisme mutlak/skeptisisme
universal dan skeptisisme nisbi/skeptisisme partikular. Skeptisisme mutlak atau
universal secara mutlak mengingkari kemungkinan manusia untuk tahu dan untuk
memberi dasar pembenaran baginya.
Jenis
skeptisisme yang mengingkari sama sekali kemampuan manusia untuk tahu dan
meragukan semua jenis pengetahuan macam-macam ini dalam praktek jarang diikuti
orang,sebab dalam kenyataan mustahil untuk dihayati. Bahkan, kaum skeptik di
zaman Yunani Kuno di atas yang kadang disebut sebagai penganut skeptisisme
mutlak, rupanya masih mengecualikan proposisi mengenai apa yang tampak atau
langsung dialami dari lingkup hal yang diragukan.
Skeptisisme
mutlak dalam praktek jarang diikuti orang karena memang merupakan suatu posisi
yang sulit dipertahankan. Posisi ini secara eksistensial bersifat kontradiktif
dan berlawanan dengan fakta yang eviden ( langsung tampak jelas dengan
sendirinya ). Pmengapa secara eksistensial bersifat kontradiktif ? karena,
seperti yang sudah ditunjukkan oleh Sokrates dalam wawancara polemisnya dengan
kaum sofis, seorang skeptik secara implisit ( dalam praktek ) menegaskan
kebenaran dari apa yang secara eksplisit ( dalam teori ) diingkarinya.
Skeptisisme
nisbi atau skeptisisme partikular tidak meragukan segalanya secara menyeluru.
Skeptisisme semacam ini hanya meragukan kemampuan manusia untuk tahu dengan
pasti dan memberi dasar pembenaran yang tidak diragukan lagi untuk pengetahuan
dalam bidang-bidang tertentu saja. Paham skeptisisme semacam ini, walaupun
tidak bersifat menggugurkan diri sendiri (
self-defeating )bagaimana skeptisisme mutlak, namun biasanya dianut karena
salah paham tentang cici-ciri hakiki pengetahuan manusia dan kebenarannya.[5]
4. Teori-teori skeptisisme
Sebagai sebuah sikap filosofis, skeptisisme memiliki
beberapa ajaran yang selalu mengalami perkembangan. Yang pertama adalah
doktrin untuk meragukan kebenaran dari setiap pengetahuan seperti yang
dikemukakan oleh Heraclites dan muridnya Cratylus. Keduanya berpendapat bahwa, “world
was in such a state of flux”. Ia sama sekali tidak permanen, sehingga
kebenaran tetap tentang segala sesuatu yang ada di dalamnya tidak bisa
ditemukan. Sikap yang kurang lebih sama juga dikembangkan oleh Socrates
(470-399 SM). Ia berkata, “.... all that i really know is that i know
nothing.” Ungkapan ini mencerminkan sikap keraguan terhadap kebenaran suatu
pengetahuan.
Teori skeptisisme yang kedua adalah tesis bahwa
tidak ada sesuatu yang pasti. Tesis ini dikembangkan oleh kaum skeptis
akademik. Menurut mereka, informasi terbaik yang bisa diambil hanyalah sebuah
kemungkinan, dan harus dihukumi berdasarkan kemungkinan juga. Doktrin
skeptisisme seperti ini juga diperkuat oleh David Hume (1711-1776 M). Ia
melihat bahwa, asumsi yang pasti, seperti hubungan antara sebab dan akibat,
hukum-hukum alam, eksistensi Tuhan dan jiwa, semuanya berada jauh dari
kepastian. Hal itu disebabkan karena pengetahuan manusia tentang hal-hal di
atas, yang kelihatannya mengandung unsur kepastian, ternyata berdasarkan pada
pengamatan dan kebiasaan belaka, yang pada hakekatnya berlawanan dengan logika.
Keterbatasan pengamatan dan kebiasaan manusia itulah yang menjadi penghalang
untuk mencapai sebuah kepastian.
Ajaran skeptisisme yang ketiga adalah,
keharusan untuk menjadikan manusia sebagai ukuran segala sesuatu (man is the
measure of all things). Dengan menjadikan manusia sebagai pusat ukuran
dalam menjustifikasi segala sesuatu, maka tidak ada lagi pengetahuan yang
disepakati secara bersama. Semuanya hanya pandangan seseorang/individu saja.
Bahkan menurut Gorgias (485-380 SM), “….nothing exists; and if something did
exist, it could not be known; and if it could be known, it could not be
communicated.” Karena yang menilai segala sesuatu adalah manusia, maka
sebenarnya pengetahuan itu tidak ada. Jikapun ada maka ia tidak bisa dipaksakan
kepada orang lain.
Teori skeptisisme yang keempat adalah keharusan
untuk selalu menghindarkan diri dari kegiatan penilaian terhadap sesuatu yang
terjadi. Ajaran ini bisa dilacak dari sekolah Pyrrho (360-272 SM). Ia dan
muridnya Timon (315-225 SM) dianggap sebagai bapak skeptisisme Yunani. Menurutnya,
memberikan penilaian terhadap sesuatu hanya akan menyebabkan kesedihan dan
gangguan mental. Kaum Pyrrhonis menganggap bahwa filosuf dogmatis dan akademis
dua-duanya tidak benar. Kelompok yang pertama mengatakan bahwa sesuatu
(pengetahuan) itu bisa diketahui, sedangkan kelompok yang lain berpendapat
bahwa tidak ada sesuatu yang bisa diketahui. Sebagai alternatif, Pyrrhonis
mengajukan sebuah sikap lain yaitu menafikan penilaian terhadap keduanya,
terkait dengan pertanyaan apakah sesuatu (pengetahuan) itu bisa diketahui atau
tidak. Sikap skeptis seperti ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Sextus
Empiricus untuk menjatuhkan argumen-argumen yang disusun oleh kaum skeptis
akademis semisal Arcesilas, Carneades, dan Aenesidemus. Sikap seperti itu, menurut
Sextus, ditujukan untuk membimbing manusia pada keadaan ataraxia; sebuah
keadaan dimana manusia mencapai ketenangan yang hakiki. Pada tahap ini, para
Pyrrhonis hidup tanpa sebuah dogma.
Ajaran skeptisisme yang kelima adalah, untuk
membangun sebuah pengetahuan, diperlukan sikap ragu yang kuat terhadap segala
sesuatu. Teori ini dikemukakan oleh filosuf Prancis Rene Descartes (1596-1650
M). Ia berpendapat bahwa jika manusia selalu meragukan (kebenaran) sesuatu,
maka di saat bersamaan, ia akan menemukan sesuatu yang tidak diragukan. Sikap
seperti ini juga digunakan untuk meragukan kebenaran semua keyakinan, yang
dengannya akan ditemukan sebuah kebenaran yang pasti. Metode inilah yang
terkenal dengan sebutan cogito ergo sum (saya berfikir, maka saya ada).
Ajaran skeptisisme yang keenam adalah
“pengetahuan obyektif itu tidak pernah ada.” Pandangan ini dikembangkan oleh
filosuf Jerman, Friedrich Nietzsche (1844-1900 M) yang diamini tokoh-tokoh
postmodernisme lainnya semisal Martin Heideger, Michel Foucault, Jacques
Derrida, Jean-Francois Lyotard, dan Richard Rorty. Mereka melihat bahwa ilmu
pengetahuan, sebagai aktivitas manusia, harus dijustifikasi berdasarkan pada
peranannya untuk kehidupan dan bukan pada standar “benar” atau “salah”, karena
menurut mereka, standar untuk menilai sebuah ilmu pengetahuan itu tidak ada.
Pandangan seperti ini juga diikuti oleh seorang filosuf Prancis Jean-Paul
Sartre (1905-1980 M), dan filosuf Amerika George Santayana (1863-1952 M).
Menurutnya, semua keyakinan –sebagai manifestasi dari pengetahuan obyektif–
bersifat irrasional. Dari sini terlihat bahwa obyektivitas sebuah pengetahuan
itu telah mati.[6]
5. Hubungan skeptisisme dengan ilmu
Upaya
dan usaha semua manusia dan khususnya para ilmuan dalam menyingkap
hakikat-hakikat segala sesuatu merupakan ciri dan pertanda bahwa manusia yang
berakal sehat (bukan para sofis dan skeptis) mempercayai dan meyakini bahwa
terdapat sesuatu yang diketahui dan terdapat pula sesuatu bisa diketahui. Dan
apa-apa yang mungkin untuk diketahui kemudian dijadikan subjek dan ranah
pembahasan dan pengkajian. Domain penyingkapan hakikat dan sejauh mana serta
pada wilayah mana saja manusia dapat menggapai pengetahuandan keyakinan. Begitu
pula dalam wilayah mana manusia tidak memiliki kemungkinan untuk dapat memahami
dan mengetahui, seperti kemustahilan dan ketidakmampuan manusia menyingkap dan
mengungkap hakikat zat Sang Pencipta.
Baik
dalam filsafat Barat maupun dalam filsafat Islam akan diperhadapkan dengan
beberapa keraguan dan kritikan dimana salah satu yang terpenting adalah
keraguan terhadap probabilitas dan kemungkinan pencapaian ilmu dan pengetahuan.
Yang pasti dalam filsafat Barat keraguan semacam itu sangatlah kental dan
bahkan telah melahirkan beberapa aliran yang secara terang-terangan mendukung
pemikiran semacam itu. Realitas ini sedikit berbeda dalam filsafat Islam dimana
hal tersebut hanyalah sebatas sebuah kritikan dimana para filosof Muslim telah
mencarikan solusi yang tepat dan jawaban yang proporsional. Kritikan ini dapat
dilihat dalam perjalanan pemikiran Al-Gazali dimana awalnya mengalami semacam
keraguan dan melontarkan berbagai kritikan pada unsur-unsur pemikiran filsafat
Islam, namun pada akhirnya dia mencapai suatu keyakinan baru dan berhasil
keluar dari kemelut pemikiran.
Berikut
ini kita berusaha akan membeberkan segala keraguan dan kritikan yang ada dan
kemudian mencarikan jawaban dan solusinya. Keraguan yang dilontarkan oleh kaum
sofis dalam ranah makrifat dan keyakinan memiliki dua bentuk;
1.
Kemampuan akal dalam menggapai hakikat sesuatu.
2. Berkaitan dengan sebagian
pengenalan-pengenalan manusia.
Keraguan
dalam bentuk pertama dapat dijabarkan secara universal sebagai berikut;
A. Alat dan sumber pengetahuan, keyakinan, ilmu, dan makrifat manusia adalah indra dan akal.
B. Indra dan akal manusia rentan dengan kesalahan, karena kesalahan penglihatan, pendengaran, dan rasa itu tidak dapat dipungkiri dan juga tidak tertutup bagi seseorang mengenai kontradiksi-kontradiksi akal serta beberapa kekeliruannya. Dalam banyak kasus di sepanjang sejarah, kita menyaksikan dalil-dalil rasional dan argumentasi-argumentasi akal telah dibangun, namun seiring berlalunya waktu secara bertahap dalil dan argumentasi tersebut satu persatu menjadi batal.
A. Alat dan sumber pengetahuan, keyakinan, ilmu, dan makrifat manusia adalah indra dan akal.
B. Indra dan akal manusia rentan dengan kesalahan, karena kesalahan penglihatan, pendengaran, dan rasa itu tidak dapat dipungkiri dan juga tidak tertutup bagi seseorang mengenai kontradiksi-kontradiksi akal serta beberapa kekeliruannya. Dalam banyak kasus di sepanjang sejarah, kita menyaksikan dalil-dalil rasional dan argumentasi-argumentasi akal telah dibangun, namun seiring berlalunya waktu secara bertahap dalil dan argumentasi tersebut satu persatu menjadi batal.
C.
Kesalahan dan kekeliruan kedua sumber pengetahuan dan makrifat tersebut dalam
beberapa hal tidaklah nampak, akan tetapi tetap saja tidak dapat dijadikan
landasan dan tertolak.
Dengan demikian, berdasarkan ketiga pendahuluan di atas yakni pengetahuan dan makrifat manusia yang dihasilkan lewat jalur indra dan akal adalah tidak dapat dijadikan pijakan dan karena manusia hanya mempunyai dua jalur dan sumber pengetahuan ini maka sangatlah logis apabila manusia meragukan apa-apa yang dipahami dan diyakininya tersebut serta sekaligus mengetahui bahwa mereka mustahil mencapai suatu keyakian dan pengetahuan yang hakiki. Atau keraguan itu bisa dipaparkan dalam bentuk ini bahwa senantiasa terdapat jarak antara manusia dan realitas atau gambaran-gambaran pikiran dan persepsi-persepsinya itu, dan pikiran manusia, sebagaimana kaca mata, merupakan hijab yang membatasinya dengan realitas eksternal, dengan demikian, tidak akan pernah manusia menyaksikan dan mengetahui realitas dan kenyataan eksternal itu sebagaimana adanya.
Kesimpulannya, kita tidak bisa benar-benar yakin bahwa realitas dan objek eksternal itu diketahui dan dipahami sebagaimana mestinya, karena mungkin saja pikiran kita telah ikut campur dalam mewarnai pemahaman dan pengetahuan tersebut dimana hal ini sebagaimana kaca mata yang berwarna telah ikut berpengaruh dalam penampakan objek-objek yang kita saksikan. Oleh karena itu, mustahil menggapai suatu keyakinan dan pengetahuan yang sebagaimana hakikatnya.
Dengan demikian, berdasarkan ketiga pendahuluan di atas yakni pengetahuan dan makrifat manusia yang dihasilkan lewat jalur indra dan akal adalah tidak dapat dijadikan pijakan dan karena manusia hanya mempunyai dua jalur dan sumber pengetahuan ini maka sangatlah logis apabila manusia meragukan apa-apa yang dipahami dan diyakininya tersebut serta sekaligus mengetahui bahwa mereka mustahil mencapai suatu keyakian dan pengetahuan yang hakiki. Atau keraguan itu bisa dipaparkan dalam bentuk ini bahwa senantiasa terdapat jarak antara manusia dan realitas atau gambaran-gambaran pikiran dan persepsi-persepsinya itu, dan pikiran manusia, sebagaimana kaca mata, merupakan hijab yang membatasinya dengan realitas eksternal, dengan demikian, tidak akan pernah manusia menyaksikan dan mengetahui realitas dan kenyataan eksternal itu sebagaimana adanya.
Kesimpulannya, kita tidak bisa benar-benar yakin bahwa realitas dan objek eksternal itu diketahui dan dipahami sebagaimana mestinya, karena mungkin saja pikiran kita telah ikut campur dalam mewarnai pemahaman dan pengetahuan tersebut dimana hal ini sebagaimana kaca mata yang berwarna telah ikut berpengaruh dalam penampakan objek-objek yang kita saksikan. Oleh karena itu, mustahil menggapai suatu keyakinan dan pengetahuan yang sebagaimana hakikatnya.
Keraguan bentuk kedua berhubungan dengan
keraguan dalam aksioma-aksioma dan dasar-dasar pengetahuan. Dalam hal ini para
filosof berupaya mengajukan berbagai solusi dan jawaban.
Keraguan-keraguan yang terlontarkan
dalam filsafat Islam adalah sebagai berikut:
1. Indra
melakukan kesalahan dan kekeliruan, sedangkan segala sesuatu yang salah dan
keliru tidak dapat dijadikan pijakan, sementara mayoritas pengetahuan dan
makrifat manusia bersumber dari indra dan empirisitas.
2. Dalam
banyak permasalahan manusia berargumentasi dan berdalil dengan akal dan
rasionya, akan tetapi setelah berlalunya waktu nampaklah berbagai kesalahan-kesalahan
argumentasi rasional itu. Oleh karena itu, kita tidak dapat bersandar pada
argumentasi dan burhan akal, pada saat yang sama kita menyaksikan bahwa begitu
banyak pengetahuan dan makrifat manusia bersumber dari akal.
3. Keberadaan
perkara-perkara yang saling kontradiksi dan bertolak belakang satu sama lain
dalam pemikiran-pemikiran manusia telah menyebabkan hadirnya sejenis keraguan
dan ketidakpercayaan pada salah sumber pengetahuan dan makrifat yakni akal dan
rasio.
4. Perbedaan
yang nyata di antara para filosofdan pemikir dalam wilayah pemikiran dan
keilmuan telah menunjukkan bahwa upaya pencapaian suatu pengetahuan dan
makrifat hakiki adalah hal yang sangat sulit atau hampir-hampir mustahil.
5. Keberadaan argumen-argumen yang sempurna dan
dapat diterima pada dua persoalan yang saling kontradiksi dan berbenturan satu
sama lain telah menampakkan kepada kita bahwa segala argumentasi akal tidaklah
nyata dan hakiki.
6. Apabila
cukup dengan keyakinan akal bahwa sesuatu itu ialah aksioma, maka hal ini bisa
diajukan suatu kritikan bahwa akal meyakini suatu perkara yang secara potensial
mengandung kesalahan, oleh karena itu, tidak mesti mempercayai perkara itu
karena sama sekali tidak berpijak pada tolok ukur. Dengan demikian, keyakinan
akal dalam aksioma-aksioma tidak valid.
7. Manusia
dalam keadaan tidur menyaksikan seluruh perkara itu nampak secara nyata dan
hakiki, akan tetapi setelah terbangun dia kemudian memahami bahwa semua yang
disaksikan tersebut hanyalah suatu hayalan dan mimpi. Maka dari itu, bagaimana
kita bisa meyakini bahwa kita sekarang ini tidak dalam keadan tidur dan
berhayal serta apa-apa yang kita saksikan tersebut bukanlah suatu mimpi belaka.
8. Manusia-manusia
yang berpenyakit dan gila menyangka bahwa perkara-perkara yang tidak riil itu
adalah perkara-perkara yang nyata dan hakiki. Dengan demikian, bagaimana kita
dapat mempercayai bahwa kita tidak sementara terjangkit suatu penyakit tertentu
atau sedang mengalami suatu kesalahan dalam sistem pemikiran dan kontemplasi.
9. Akal
mampu menampakkan kesalahan dan kekeliruan indra, namun apakah kita yakin bahwa
tidak terdapat sesuatu atau perkara lain yang dapat menunjukkan secara jelas
kesalahan dan kekeliruan akal itu.
10. Jumlah
aksioma-aksioma itu sangatlah terbatas dan semuanya berpijak pada satu
proposisi yakni "kemustahilan bergabungnya dua perkara yang saling
berlawanan". Proposisi ini bersandar pada konsepsi tentang ketiadaan dan
kemustahilan yang terdapat dalam proposisi itu (kemustahilan bergabungnya …)
dimana akal tidak mampu memahaminya, karena kemustahilan itu sendiri tidak
mempunyai individu-individu dan objek-objek eksternal.
11. Keragaman
dan perbedaan dalam karakteristik dan potensi setiap individu, lingkungan dan
ekosistemnya, dan budaya-budayanya telah menyebabkan munculnya berbagai
persepsi-persepsi dan pandangan-pandangan yang juga beragam.
12. Menyingkap
sesuatu yang tidak diketahui adalah hal yang mustahil, mengungkap suatu hakikat
merupakan hal yang tak mungkin, karena hakikat itu tak diketahui.
13. Pengetahuan
hudhuri dipandang sebagai pengetahuan yang paling tinggi dan sempurna.
Pengetahuan kepada diri sendiri adalah bersifat hudhuri, sementara semua orang
tidak bisa mengetahui "hakikat diri sendiri" dan tidak mampu
menyelami esensi "pengetahuan kepada diri sendiri" itu. Dengan
demikian, kita pun tidak mungkin mengetahui segala sesuatu selain "diri
kita sendiri".
14. Pencapaian
konsepsi-konsepsi di luar dari batas iradah dan kehendak kita, karena hal ini
menyebabkan kita mengetahui sesuatu yang telah kita ketahui sebelumnya atau
mengetahui sesuatu yang mutlak tidak diketahui, kedua konsekuensi ini adalah
batil. Dengan demikian, pembenaran sesuatu yang aksioma adalah mustahil, oleh
karena itu, tertutup jalan untuk meraih keyakinan.
15. Semakin
kita menyelami realitas dan hakikat sesuatu maka yang dihasilkan tidak lain hanyalah
persepsi itu sendiri. Oleh karena itu, yang bisa ditegaskan hanyalah "diri
kita" dan "persepsi kita", inilah makna dari suatu pernyataan
bahwa "satu-satunya realitas eksternal yang kita miliki" tidak lain
adalah persepsi itu sendiri.
16. Apabila
pengetahuan dan makrifat manusia bersifat penyingkapan dan pencerminan terhadap
objek-objek eksternal, maka tidak mungkin terdapat kesalahan.
17. Manusia
di awal kelahirannya sama sekali tidak memiliki pengetahuan dan jahil terhadap
aksioma-aksioma. Oleh karena itu, aksioma-aksioma tersebut dihasilkan oleh
manusia setelah berinteraksi secara luas dengan alam dan lingkungannya, aksioma
bukanlah merupakan fitrah dan pembawaan alami manusia.
Sementara
keraguan-keraguan yang muncul dalam tradisi filsafat Barat antara lain:
1. Indra
dan akal melakukan kesalahan dan kekeliruan, oleh karena itu tidak dapat
dijadikan landansan.
2. Terdapat
kontradiksi-kontradiksi antara akal itu sendiri dan manusia yang berakal dalam
wacana filsafat.
3. Menegaskan
setiap sesuatu niscaya membutuhkan serangkaian dasar-dasar, dan membuktikan
dasar-dasar itu mesti memerlukan pendahuluan-pendahuluan, demikianlah
seterusnya hingga tak terbatas. Konklusinya, perolehan makrifat dan pengetahuan
ialah hal yang tak mungkin.
4. Metode
induksi tidak menghasilkan suatu keyakinan.
5. Adanya
perbedaan riil pada indra-indra manusia serta perbedaan persepsi di antara
indra-indra itu, perbedaan di antara manusia-manusia dari dimensi tubuh dan
jiwa, pertentangan indra-indra, perbedaan syarat-syarat yang menyebabkan pula
lahirnya perbedaan pada persepsi-persepsi indrawi, perbedaan benda-benda dari
dimensi jarak dan tempat, perbedaan benda-benda dari aspek horizontal yakni
benda satu di atas dan benda yang lain di bawah, dan perbedaan hukum-hukum adab
dan etika. Kesemua perbedaan tersebut berkonsekuensi bahwa tak satupun ilmu dan
makrifat dapat dihasilkan.
6. Fenomena-fenomena
akibat (ma'lul) dan tanda-tanda sebab ('illah) tidaklah tersembunyi, karena
semua manusia menyaksikan bahwa fenomena-fenomena itu adalah sama, akan tetapi,
terdapat perbedaan dan keragaman dalam penentuan sebab-sebabnya.
7. Apakah
kita benar-benar yakin bahwa tidak dalam keadaan tidur dan bermimpi.
8. Adanya kemungkinan kita ditipu oleh setan.
9. Proposisi yang berbunyi, "A ada",
yakni "Saya mengetahui keberadaan A itu", dengan demikian, selain
"saya" dan persepsi-persepsi "saya" adalah sesuatu yang
tidak dapat dibuktikan keberadaanya.
10. Tidak
terdapat perbedaan antara "kualitas pertama" dan "kualitas
kedua", sebagaimana "kualitas pertama" seperti warna dan bau
adalah tidak hakiki, begitu pula "kualitas kedua" seperti panjang dan
bentuk adalah juga tidak hakiki.
11. Prinsip
kausalitas itu merupakan buatan pikiran semata, karena konsepsi-konsepsinya
bersumber dari pikiran yang tidak diperoleh lewat indra-indra yang lima itu.
12. Pikiran
manusia sama seperti kaca mata, atau fungsinya menimal sama dengan kaca mata.
Oleh karena itu, tak satupun dari persepsi-persepsi yang dapat dipercaya.
13. Mungkin
pikiran kita sama saja dengan suatu wadah yang menerima dan menyimpan apa saja
yang diberikan padanya, maka dari itu, kesalahan persepsi-persepsi tidak semua
dapat ditegaskan dan dibuktikan secara nyata.[7]
FOOTNOTE
[1] Donald M.
Borchert, Editor in chief, Encyclopedia of Philosophy, Second Edition,
Volume 9, (MacMillan Reference USA, 2006), hlm. 47.
[3] J. Sudarminta, Epistimologi Dasar, ( Yogyakarta : Kanisiur Cempaka, Cetakan ke
9, 2005 ), hlm 47
[4] Ibid, hlm. 48-49
[6] Dr. P.
Hardono Hadi, Epistimologi Filsafat
Pengetahuan, ( Yogyakarta : Kanisiur Cempaka, Cetakan ke 7, 2005 ), hlm 19
[7] Ibid, hlm.
25
BAB III
KESIMPULAN
Skeptisisme
merupakan penalaran pikiran yang tidak bisa nyata dalam imajinasi kita hanya
bisa di lihat dari mimpi, halusinasi kesadaran kita, dll. Skeptisisme dalam
sejarahnya merupakan imajinasi seorang ilmuan yang merupakan ide-ide yang logis
dalam pemikirannya itu sendiri.
Skeptisisme
hanya dibedakan berdasarkan tema keraguannya, tetapi juga berdasarkan lingkup
bidang yang diragugannya. Biasa dibedakan antara skeptisisme mutlak/skeptisisme
universal dan skeptisisme nisbi/skeptisisme partikular. Skeptisisme mutlak atau
universal secara mutlak mengingkari kemungkinan manusia untuk tahu dan untuk
memberi dasar pembenaran baginya.
Skeptisisme
nisbi atau skeptisisme partikular tidak meragukan segalanya secara menyeluru.
Skeptisisme semacam ini hanya meragukan kemampuan manusia untuk tahu dengan
pasti dan memberi dasar pembenaran yang tidak diragukan lagi untuk pengetahuan
dalam bidang-bidang tertentu saja. Paham skeptisisme semacam ini, walaupun
tidak bersifat menggugurkan diri sendiri (
self-defeating )bagaimana skeptisisme mutlak, namun biasanya dianut karena
salah paham tentang cici-ciri hakiki pengetahuan manusia dan kebenarannya.
Teori
skeptisisme. Yang pertama adalah doktrin untuk meragukan kebenaran dari
setiap pengetahuan seperti yang dikemukakan oleh Heraclites dan muridnya
Cratylus. skeptisisme yang kedua adalah tesis bahwa tidak ada sesuatu
yang pasti. Tesis ini dikembangkan oleh kaum skeptis akademik. Ajaran
skeptisisme yang ketiga adalah, keharusan untuk menjadikan manusia
sebagai ukuran segala sesuatu (man is the measure of all things). Teori
skeptisisme yang keempat adalah keharusan untuk selalu menghindarkan
diri dari kegiatan penilaian terhadap sesuatu yang terjadi. Ajaran ini bisa
dilacak dari sekolah Pyrrho (360-272 SM). Ia dan muridnya Timon (315-225 SM)
dianggap sebagai bapak skeptisisme Yunani. Ajaran skeptisisme yang kelima adalah,
untuk membangun sebuah pengetahuan, diperlukan sikap ragu yang kuat terhadap
segala sesuatu. Teori ini dikemukakan oleh filosuf Prancis Rene Descartes
(1596-1650 M). Ajaran skeptisisme yang keenam adalah “pengetahuan
obyektif itu tidak pernah ada.” Pandangan ini dikembangkan oleh filosuf Jerman,
Friedrich Nietzsche (1844-1900 M).
DAFTAR
PUSTAKA
Donald M. Borchert, Editor in chief, Encyclopedia
of Philosophy, Second Edition, Volume 9, (MacMillan Reference USA, 2006)
J. Sudarminta, Epistimologi
Dasar, ( Yogyakarta : Kanisiur Cempaka, Cetakan ke 9, 2005 )
Dr. P. Hardono Hadi, Epistimologi Filsafat Pengetahuan, ( Yogyakarta : Kanisiur Cempaka,
Cetakan ke 7, 2005 )
Tag :
MAKALAH

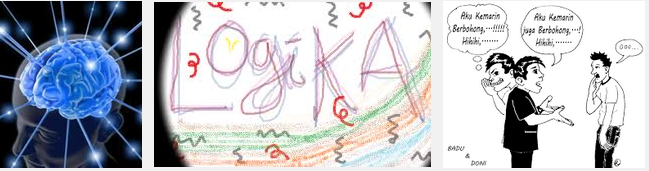

0 Komentar untuk "MAKALAH LOGIKA SAINTIFIK SKEPTISISME"